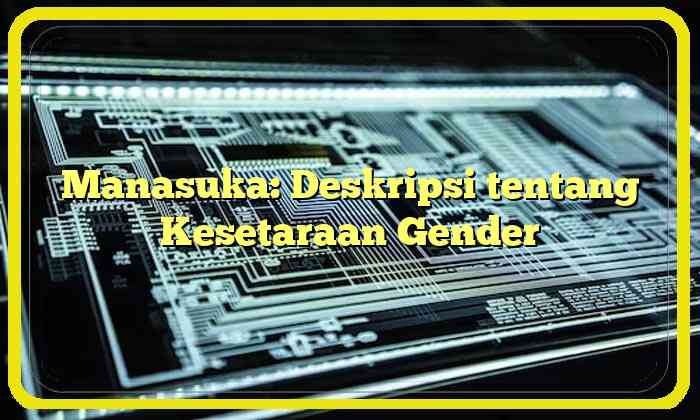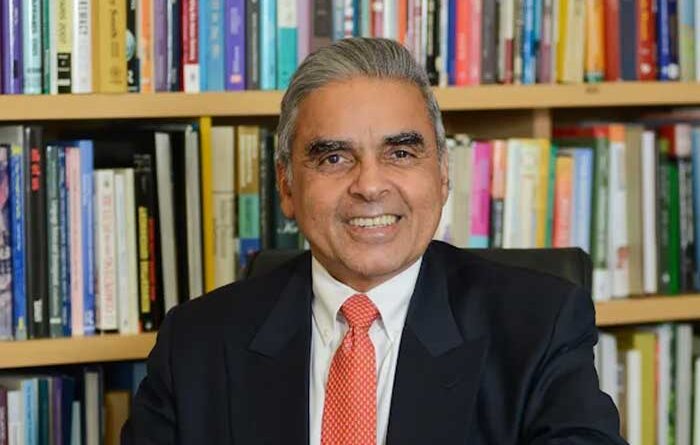
Judul di atas sengaja saya adopsi dari judul buku pemikir Asia progresif Kishore Mahbubani, Can Asians Think? yang edisi Indonesianya diterjemahkan menjadi, Bisakah Orang Asia Berpikir? (2005). Provokatif memang. Mahbubani sendiri menyebutnya, ‘pertanyaan sensitif. Disebut provokatif dan sensitif karena berkaitan dengan harga diri atau martabat suatu bangsa dan ras tertentu: siapa pula yang rela jika diragu-kan kemampuan berpikirnya?
Namun, Mahbubani tidak sedang berolok-olok. Dia justru menampar kita untuk bangkit. Bukankah Asia (Timur) dalam sejarah dunia pernah menjadi ternpat bersemainya peradaban-peradaban agung dengan pemikirannya yang adiluhung? Sebut saja Persia, Mesopotamia, Baghdad, Tiongkok, India, atau bahkan nu-santara.
Agama-agama besar yang banyak dianut manusia di dunia juga,tumbuh dari benua Asia (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu). Tapi, mengapa beberapa abad ke belakang justru Asia (Timur) yang membebek pada Barat? Tesis Mahbubani mengatakan, seseorang (atau komunitas) yang bisa berpikir tidak akan ikhlas didikte pihak lain yang dulunya justru belajar pada dirinya. Inilah yang kemudian menjadi tonggak pemikiran bahwa Asia sedang merintis kebangkitannya kembali dengan Tiongkok dan India menjadi lokomotifnya.
Sebenarnya, Mahbubani ingin mengajak kita untuk berbicara sesuatu yang sangat makro (peradaban Asia). Namun, saat memberi kata pengantar versi Indonesia untuk buku ini, Dawam Rahardjo mengontekstualisasikan pemikiran Mahbubani itu menjadi, “Mampukah orang Indonesia berpikir?” Sebab, kita terlampau sering disuguhi ‘spiral-spiral kebodohan’: krisis yang berulang, konflik yang berulang, blunder yang berulang, dan sebagainya.
Padahal secara historis, Indonesia sebagai pewaris nusantara adalah bangsa yang punya tradisi berpikir kuat. Tapi, mengapa kita sekarang dengan mudah ‘ditipu’ negara lain. Jangankan Amerika Eropa, oleh Malaysia, Singapura, atau bahkan Vietnam kita kerap “dikerjai” dalam berbagai hal (terutama ekonomi-politik). Seperti mengamini tesis Anthony Giddens (2002), bahwa kematian sebuah peradaban selalu diawali dari krisis refleksi masyarakatnya, benarkah bangsa kita mengalami kematian reflektif ?
Mobil Kiat Esemka membantah kekhawatiran itu. Ternyata orang Indonesia masih ada yang bisa berpikir-reflektif. Terlepas dari pro dan kontra dari sisi politik, fenomena Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo dan Kiat Esemkanya itu telah menjadi bukti jika kita mau, kita pasti bisa. Bahkan, ternyata tidak hanya Solo, di Surabaya dan Semarang juga mulai bermunculan SMK-SMK yang merintis pembuatan produk otomotif lokal serupa Kiat Esemka.
Jika ditanya apa yang menjadi resep sehingga para produsen mobil lokal itu dalam istilah Mahbubani bisa berpikir? Jawabannya adalah kemauan untuk belajar (berpendidikan). Terkesan klise memang. Tapi, hal ini tidak sederhana jika coba kita kaitkan dengan fenomena yang berlangsung di India sehingga bisa sukses menapaki rute menuju negara maju layaknya Jepang di masa lalu atau Tiongkok di masa kini.
Belajar dari India
Napak tilas kesuksesan Tiongkok menjadi calon ‘raja dunia’ mungkin sudah banyak diulas. Namun, kupasan tentang India sebagai kandidat ‘macan ekonomi’ dunia belum banyak dilakukan. Padahal, India, seperti halnya Indonesia, juga menyimpan banyak problem sosial-politik: negara penganut demokrasi dengan jumlah populasi yang besar, tapi ting-kat kemiskinan dan korupsinya juga besar. Bedanya, sementara Indonesia masih jalan di tempat, India sudah berjalan di track yangtepat untuk pemberantasan korupsi dan pengurangan kemiskinan. Di sinilah relevansi kita belajar dari India.
Pendidikan (kesadaran literasi) di India merupakan prinsip fundamental yang telah terlembagakan dalam kebijakan negara dan budaya masyarakat setempat. Selama di India, kami sudah banyak menemui orang-orang India yang menghabiskan waktu dengan membaca di mana pun mereka berada.
Jika kita menggunakan Metro (MET di Delhi), tidak sedikit dari mereka yang mengisi waktunya dengan membaca. Secara umum, orang India lebih gemar membaca daripada orang Indonesia. Mungkin bacaan anak-anak SMA di India lebih baik secara kualitas dan kuantitas daripada bacaan mahasiswa Indonesia. Di India, bacaan bermutu lebih mudah didapatkan dengan harga yang tidak mahal pula.
Riset Novian Widiadharma. Mahasiswa Program Doktor Filsafat Timur di Delhi University (2010) mungkin bisa dijadikan rujukan. Terkait makna ilmu dan pengetahuan bagi orajig India, Novian melacak sampai jauh ribuan tahun ke belaMang. Novian . akhirnya menemukan bahwa terminologi pengetahuan merupakan nomenklatur khas dari peradaban India kuno, yang tetap terlembagakan dalam agama dan filsafat yang mereka anut hingga saat ini.
Pengetahuan bisa dikatakan adalah segalanya bagi orang India. Menurut mereka, bila orang ingin selamat atau mencapai kelepasan spiritual, ia memerlukan pengetahuan; bila ingin bahagia di dunia, ia juga membutuhkan pengetahuan, semuanya bergantung pada pengetahuan.
Mengunggulkan pengetahuan
Dalam sistem kasta Hinduisme India, kita mengenal kasta Brahmana adalah kasta tertinggi dibandingkan ketiga kasta yang lain. Mengapa? Bukankah kekuasaan ada di tangan kasta Ksatria? Atau kekayaan ada di kasta Vaisya? Ternyata, walaupun kekuasaan ada di tangan para Ksatria dan kekayaan ada di genggaman Vaisya, namun pengetahuan dan kebijaksanaan ada sepenuhnya di tangan kaum Brahmana. Ini me-nunjukkan superioritas pengetahuan di atas kekuasaan dan kekayaan. Pengetahuan adalah kebijaksanaan, kuasa dan kekayaan sekaligus.
Dampaknya dahsyat. Jumlah guru besar dan doktor India yang ada saat ini sudah lebih dari 500 ribu orang. Bandingkan dengan data Direktori Doktor Indonesia yang mencatat jumlah doktor di Indonesia .hanya 5.467 orang. Selain itu, karya-karya penelitian kampus-kampus India luar biasa. Satu kampus saja bisa menghasilkan lebih dari 1.500 karya tulis dalam satu tahun. Sementara, di Indonesia satu kampus hanya menghasilkan maksimal ratusan karya tulis.
Sebagai hasil dari kualitas pendidikan yang bermutu tersebut, tidak kurang dari 30 persen peneliti NASA adalah orang India, begitu juga staf ahlldi Microsoft Corporation dan perusahan-perusahaan besar di berbagai negara lainnya adalah para ahli dari India.
Para pemikir sosial-politik he-bat juga banyak berasal dari India. Sebut saja Amartya Sen, ekonom peraih Nobel ekonomi 1998, Ra-bindranath Tagore, penerima Nobel kesusastraan 1913, dan juga Kishore Mahbubani sendiri. Meski besar di Singapura, Mahbubani adalah keturunan India.
Imbas positif itu juga dirasakan di dalam negeri. Untuk kebutuhan dalam negeri. India sudah mulai memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi, misalnya mobil, pesawat, senjata, kapal selam (alutsista), dan sebagainya. Dengan demikian, tidak sulit bagi India untuk mendeklarasikan dirinya telah mampu berdikari mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Apakah hal serupa bisa terjadi di Indonesia? Tentu sangat bisa. Dengan catatan, para elite politik dan ekonomi kita, para pengambil kebijakan kita, mau untuk berpikir. Sebab, selama ini tampak-nya para elite kita ini dalam kriteria Mahbubani tidak bisa berpikir.
AbdulAllamAmrullah
Bisakah Orang Asia Berpikir?